“Aku rasa aku baru tahu perasaan mabuk cinta itu bagaimana.” Ujarku sambil tangan ligat menyiapkan sarapan untuk keluarga.
“Kau sedang mabuk cinta, Arini? Pantas saja kau sering mengelamun. Lagi rindukan kekasih rupanya.” Rani memandangku dengan matanya yang bulat. Antara terkejut dan mahu mengusik.
“Bukan aku, Sundara.” Aku membalas usikan Rani dengan menyebut namanya yang jarang disebut. Rani Sundara. Itulah nasib anak yang mempunyai ibu yang gilakan filem hindi.
Rani menjeling tajam. Siapa suruh panggil aku Arini. Tidak ada satu manusia pun yang memanggil aku Arini kecuali... ah, lupakan!
“Kau tahukan aku lagi baca buku tentang Mawlana Rumi? Tulisannya... subhanallah... terlalu sempurna terjemahan hatinya. Jelas tergambar dirinya yang mabuk cinta total!”
Rani mengambil sekeping roti bakar lalu duduk ditangga.
“Satu hal yang aku belajar, kita tak akan mampu tulis perihal sesuatu dengan sebegitu baik kalau perasaan kita bukanlah begitu. Maksudku, kita tidak akan berupaya menulis tentang pedihnya patah hati sekiranya kita terlebih dulu tidak merasakannya, kan? Atau jika kita ditimpa penyakit kronik... mana mungkin kita boleh bercerita dengan jelas bagaimana sakitnya penyakit itu kalau kita sendiri tidak alaminya. Jadi, begitulah tulisan Rumi. Beliau bercerita tentang cinta dan kemabukan yang ada di dalamnya. Betapa menyembah Tuhan itu adalah satu ibadah yang memabukkan. Pastilah... beliau tidak akan berjaya menghasilkan karya yang begitu jelas dalam cintanya kalau beliau tidak memandang dan merasa cinta Tuhan dengan sebegitu asyik. Dan keasyikan itu cuma boleh diperoleh dengan ibadah yang sahih dan bebas dari keinginan duniawi.” Suara aku beransur perlahan di penghujung bicara. Terasa hati disentak dengan suara sendiri.
“Sufi...” Rani bersuara.
“Iya?” Aku memandangnya sambil meneruskan kerja.
“Sufi.” Rani sekali lagi menyebut namaku.
“Iya, kenapa kau Rani?” Suara aku sedikit tinggi. Tidak mengerti dengan Rani.
“Tidak. Aku maksudkan Rumi itu. Rumi itu seorang sufi. Merindui pertemuan dengan Tuhan adalah ibadah mereka. Dan kita masih lagi berkira-kira mahu mati.”
“Dalam.” Aku berkata sepatah. Cukuplah untuk respon kepada setiap butir perkataan Rani. Makin dalam pula bicara pagi hari ini. Masing-masing mula tenggelam dalam fikiran sendiri. Sesekali kedengaran bunyi kaki ayam yang sedang menguis tanah. Inilah yang indah tentang hidup di kampung, kita dikelilingi nyawa selain manusia!
“Oh, kau tahu, aku pernah menulis di blog tentang tokoh yang aku kagumkan iaitu Aisyah binti Talhah dan aku memberikan analogi bahawa aku ialah bulan dan beliau ialah matahari. Kau tahu kenapa?”
“Kenapa?”
“Sebab cahaya bulan datang dari matahari. Jadi, begitulah kita dalam mencontohi guru. Qudwah yang kita ikut itu asalnya dari mereka dan kita cuma menunjukkan kembali. Seperti bulan terang di langit malam. Cantiknya bulan kerana cahaya matahari yang dipancarkan kepadanya. Ternyata Rumi juga memberi analogi yang sama tentang gurunya! Aku sedikit teruja sebab asal analogi itu memang asli dari otakku sewaktu menuliskannya pada Ramadhan 2012 yang lalu, bukan aku merujuk kepada tulisan-tulisan orang lain. Jadi, gila benar perasaan teruja ini bila tahu Rumi juga menulis hal yang sama.”
“Kau semakin menarik di mataku, Sufi Arini.” Rani memandangku dengan senyum yang manis. Mengada-ngada!
Aku menyambung lagi, “Rumi suka menggunakan ungkapan dan lambang yang ada hubungannya dengan cahaya. Baginya Tuhan boleh diumpamakan sebagai matahari yang terang-benderang. Al-Ghazali dalam kitab tasawufnya, Misykat Al-Anwar juga mengumpamakan Tuhan dengan “Matahari” dan manusia ialah bulan yang mendapat pantulan sinarnya. Rumi, untuk menyebut nama guru mistiknya, Syamsuddin dari Tabriz, berganti-ganti beliau menggunakan kalimat “matahari” dan “bulan”. Bila Rumi mengisahkan pertemuan dengan sahabat dan gurunya dari Tabriz itu, dalam suasana ekstasi mistis, beliau lebih sering menyebut Syamsuddin dengan “matahari”, di samping erti dari “Syamsi” itu sendiri memang matahari. Namun, yang dimaksudkan oleh Rumi adalah orang yang mencapai makrifat atau dekat dengan Tuhan. Sedangkan kalau beliau mengisahkan tentang kerinduan untuk bertemu guru dan Tuhan, Rumi lebih suka menyebut gurunya sebagai ‘bulan” yang memberi erti peribadi yang mendapat cahaya dari Tuhan. Menarik bukan?”
“Aku juga pernah membaca tulisannya tentang kehidupan di dunia yang diumpamakan dengan malam hari. Pada malam hari, yang ada ialah bulan yang sering ditutupi mendung iaitu nafsu-nafsu yang menyesatkan. Untuk melihat cahaya bulan itu, seseorang haruslah menyingkirkan mendung yang meliputi diri dan penglihatannya.” Rani menyambung teruja.
“Wah, itulah juga yang aku baca! Aku belum habis fikir... lagak apakah jiwa Rumi ini? MasyaAllah... membacanya saja aku jadi rindukan Tuhan. Tulisan seorang kekasih sememangnya paling berjaya menerobos...” Kata-kataku dihentikan oleh jeritan ibu dari ruang tamu. Aku dan Rani saling berpandangan. Ketawa meletus.
“Masuk ke hati pembaca. Dan jeritan ibu langsung masuk ke telinga kau.” Rani mula bangun untuk ke ruang tamu dengan ketawa yang masih tersisa. Aku mengangkat dulang makanan. Senyuman masih setia singgah dibibir.
Setelah begitu lama,matahari tidak pernah bilang pada bulan,
“kau berhutang kepadaku”.
Lihat apa yang terjadi dengan cinta seperti ini,ia menyalakan langit!
- Mawlana Rumi
Terima kasih, untuk engkau seorang darwisy yang ibadahmu terlalu terang sehingga jalan untukku dihala jelas ketika aku lagi teraba-raba di dalam gelap.
Baarakallahu fiik.
Kuantan, 1 Januari 2017 | © meremuna
------------
Belajar Hidup Dari Rumi - Serpihan-serpihan Puisi Penerang Jiwa, Haidar Bagir.
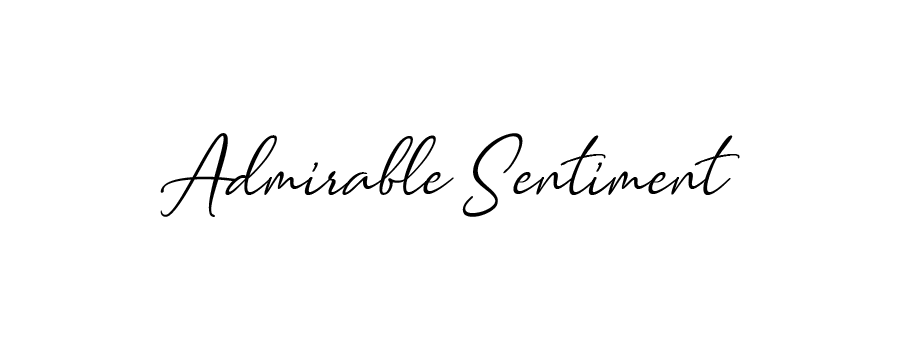
0 comment(s)
“Hanya sedikit ini yang kutahu, kutulis ia untuk-mu, maka berbagilah dengan-ku apa yang kau tahu.”